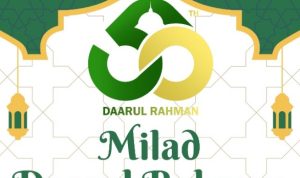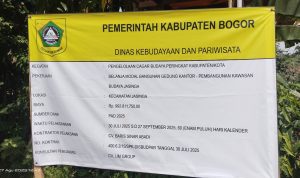Publikbicara.com – Di tengah belantara beton dan dengung mesin pabrik di Kecamatan Klapanunggal, terselip sebuah kampung yang belum sepenuhnya menyerah pada riuh zaman.
Kampung Cipari, begitulah orang menyebutnya. Di sanalah, di sebuah sudut tanah yang tenang, berdirilah sebuah saung. Bukan saung biasa, melainkan Saung Kalingga tempat di mana warisan leluhur dibangkitkan kembali dari tidur panjangnya.
Bulan April 2024 menjadi saksi, ketika beberapa pasang tangan yang masih setia pada akar budaya mulai menanam benih harapan. Latar belakangnya sederhana, yakni kegelisahan.

Mereka gelisah melihat anak-anak yang tak lagi mengenal karinding, pemuda yang lebih fasih lagu K-Pop daripada pupuh Sunda, dan seniman yang perlahan kehilangan panggungnya.
Maka lahirlah Saung Kalingga, bukan hanya sebagai bangunan beratap ijuk dan berdinding kayu, tapi sebagai simbol perlawanan yang lembut melawan lupa.
Tagline-nya terdengar seperti mantera “Dina Budaya Urang Napak, Dina Budaya Urang Ngapak.”
Sebuah kalimat yang mengandung makna dalam bahwa kita harus berpijak pada budaya, mengakar, lalu menjelajah dunia tanpa kehilangan arah.
Di Saung Kalingga, suara tarawangsa mengalun setiap sore. Anak-anak desa duduk bersila, mata mereka berbinar saat petikan kacapi dan tiupan suling membentuk harmoni yang nyaris punah.

Seorang kakek dengan rambut memutih mengajarkan mereka bangreng, bukan sekadar tari, tapi tentang menghormati tanah, langit, dan air.
Di pojok lain, beberapa pemuda membuat karinding, meniupnya sambil tertawa, seolah-olah suara bambu itu adalah jantung dari masa kecil yang hampir hilang.
Tiap Sabtu sore, saung itu berubah menjadi panggung kecil. Tak megah, tapi penuh makna.
Masyarakat berkumpul, menonton pertunjukan, kadang ikut bernyanyi, kadang menitikkan air mata.
Semua orang tua, muda, petani, guru, bahkan tukang ojek merasa memiliki tempat itu.

Saung Kalingga telah menjelma menjadi ruang bersama, tempat siapa pun boleh pulang dan belajar mengenal dirinya sendiri lewat budaya.
Saung Kalingga bukan sekadar tempat belajar seni. Ia adalah rumah bagi mereka yang percaya bahwa budaya bukan warisan museum, melainkan napas yang harus terus dihidupkan.
Di sana, tradisi tidak dibekukan, tetapi diolah, dikembangkan, dan diberi ruh baru.
Visi mereka sederhana: menjadi pusat regenerasi seni dan budaya Nusantara. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi tekad baja.
Mereka menyusun misi, bukan dengan jargon kosong, melainkan dengan kerja nyata mengadakan pelatihan tarian dan musik tradisional, membangun komunitas seniman, menggelar pertunjukan keliling, menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, serta membuka ruang bagi inovasi seni yang tak tercerabut dari akarnya.

Dari terbang hingga angklung buncis, dari ketuk tilu hingga degung, semuanya hidup kembali di tangan mereka.
Kini, Saung Kalingga tak berjalan sendiri. Ia mengajak siapa saja untuk bergabung. Para pemuda yang ingin berkarya, ibu-ibu yang ingin menanamkan nilai budaya pada anaknya, sekolah-sekolah yang haus akan edukasi lokal, hingga event organizer yang mencari sajian otentik—semua dipersilakan masuk.
Bersama, mereka menulis ulang narasi masa depan. Bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan merangkulnya. Karena di tanah tempat Saung Kalingga berdiri, ada keyakinan yang tumbuh bahwa budaya bukan beban sejarah, melainkan cahaya yang menuntun langkah.
Dan di sanalah, di antara denting kacapi dan langkah tarian, kita menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya.***