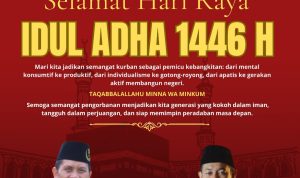Literasirakyat.com – Dalam banyak narasi politik Indonesia, masyarakat kelas bawah petani, buruh, nelayan, pedagang kecil sering kali hanya muncul saat pemilu. Mereka didatangi, dijanjikan, lalu dilupakan.
Padahal, pengalaman hidup mereka justru mencerminkan denyut politik yang paling nyata: perjuangan sehari-hari untuk bertahan di tengah ketimpangan dan ketidakadilan struktural.
Inilah yang disebut sebagai politik akar rumput, politik yang tumbuh dari bawah, dari kesadaran kolektif warga terhadap realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi.

Sayangnya, kekuatan ini cenderung terpinggirkan oleh dominasi elite yang menguasai jalur-jalur formal kekuasaan—baik lewat partai politik, birokrasi, hingga konglomerasi ekonomi.
Politik dari bawah bukan sekadar suara pemilu
Banyak yang mengira politik hanya terjadi di ruang-ruang formal gedung parlemen, meja musyawarah, atau arena kampanye.
Padahal, sebagaimana dijelaskan James C. Scott dalam Weapons of the Weak (1985), masyarakat bawah memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan sikap politik mereka melalui perlawanan diam, pengorganisasian komunitas, hingga aksi kolektif yang kadang tak terliput media.

Namun, ketika politik direduksi hanya pada kontestasi suara, masyarakat akar rumput kehilangan ruang untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara substansial.
Lebih parah lagi, agenda pembangunan sering kali justru dimonopoli oleh elite yang memiliki akses pada kekuasaan.
Salah satu indikatornya bisa dilihat dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2020) yang menyebutkan bahwa biaya kampanye kepala daerah bisa mencapai Rp25 miliar.

Ini membuka ruang bagi politik balas budi antara kandidat dan pemodal.
Akibatnya, kebijakan yang seharusnya melayani rakyat justru diarahkan untuk melindungi kepentingan elite ekonomi.
Ketimpangan kebijakan dan peran oligarki
Penelitian Jeffrey Winters dalam Oligarchy (2011) menggambarkan bagaimana segelintir orang kaya bisa mendominasi demokrasi dengan kekuatan ekonomi mereka. Dalam konteks Indonesia, ini bukan teori semata.
![]()
Studi dari Indikator Politik Indonesia (2022) menunjukkan bahwa hanya 38% masyarakat yang percaya wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan mereka.
Ketidakpercayaan ini mencerminkan jarak yang makin lebar antara rakyat dan pengambil keputusan.
Situasi ini mengindikasikan bahwa banyak kebijakan pembangunan tidak dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat bawah, melainkan berdasarkan skenario yang ditentukan oleh elite politik dan bisnis.

Gerakan akar rumput bisa menjadi kekuatan tanding.M eski demikian, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari bawah.
Dari perjuangan petani dalam mempertahankan lahan, advokasi buruh migran, hingga gerakan lingkungan di Kendeng dan Wadas, semua itu merupakan bentuk politik akar rumput yang menolak tunduk pada logika kekuasaan dominan.
Namun gerakan ini masih sporadis dan tidak terkoordinasi. Di sinilah pentingnya revitalisasi politik akar rumput.
Artinya, bukan hanya memperkuat suara masyarakat, tapi juga membangun struktur organisasi, pendidikan politik, dan jaringan solidaritas yang mampu melawan sistem yang tidak adil.

Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) menekankan pentingnya kesadaran kritis agar masyarakat tidak hanya menerima keadaan, tetapi mampu menganalisis dan mengubahnya.
Menuju demokrasi yang lebih inklusif
Jika kita menginginkan demokrasi yang lebih sehat dan berpihak pada rakyat, maka penguatan politik akar rumput bukan sekadar opsi melainkan keharusan.
Tidak cukup hanya mengandalkan lembaga formal atau elite politik untuk membawa perubahan. Rakyat harus dilibatkan secara aktif, kritis, dan terorganisir.

Revitalisasi politik akar rumput bukan hanya upaya melawan korupsi dan ketimpangan, tetapi juga cara untuk menghidupkan kembali demokrasi itu sendiri.
Demokrasi yang bukan hanya milik mereka yang punya modal dan akses, tapi milik semua orang—terutama mereka yang selama ini disingkirkan.
Sebagai informasi, berikut Referensi catatan bertajut Mengapa Politik Akar Rumput Harus Diperkuat di Tengah Dominasi Elit.

Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.
Winters, J. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Kajian Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Indikator Politik Indonesia. (2022). Survei Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Negara.***